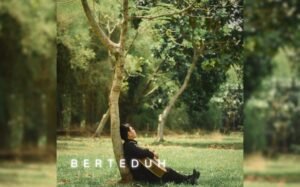Oleh: Mukani – Dosen STAI Darussalam Krempyang Nganjuk
Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan Belanda ke Sulawesi tahun 1830, banyak anggota laskarnya meneruskan perjuangan tidak dengan perjuangan fisik. Namun dengan merubah strategi perlawanan untuk menyebar dan berdiaspora dalam meneruskan kaderisasi. Mereka melakukan perlawanan secara kultural. Menurut Zainul Milal Bizawie dalam buku Jejaring Ulama Diponegoro (2019), mereka melakukan gerakan literasi dan memperkuat pemahaman keagamaan terhadap masyarakat. Bentuknya dengan mendirikan masjid, pesantren ataupun lembaga pendidikan Islam lainnya.
Mereka ini kemudian berpencar ke seluruh penjuru mata angin. Para sisa laskar Diponegoro banyak yang melarikan diri ke daerah Jawa Tengah sebagai Pinggiran Nagari. Sebagian ke arah barat sebagai Mancanegara Kulon dan sebagian lagi ke daerah Jawa Timur sebagai Mancanegara Wetan. Salah satunya Mbah Canthing, yang makamnya berada di pojok Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.
Perjuangan
Pada tanggal 25-27 September 2019 digelar The 3rd International Workshop and Training on Islam Nusantara Reasearch Metodology. Lokasinya di kampus Universitas Yudharta Pasuruan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Asosiasi Penulis dan Peneliti Islam Nusantara Seluruh Indonesia (Aspirasi). Peserta yang hadir ada dari Mesir, Belanda, Inggris, Amerika, Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam. Di samping perwakilan berbagai kampus dari seluruh pelosok Indonesia.
Penulis mempresentasikan artikel berjudul Mbah Canthing dan Jejak Nasionalisme Santri. Mengutip keterangan Murhardi/Partoko (2011), cerita kedatangan Mbah Canthing hingga sampai ke Desa Mlorah dibenarkan olehnya. Dia adalah mantan kepala Desa Mlorah selama dua periode, sehingga tahu persis sejarah awal desanya.
Pensiunan PNS guru Penjaskes ini memperoleh cerita secara turun temurun. Cerita itu pernah dimuat surat kabar MediaRakyat Post edisi 15 bulan Oktober 2011 berjudul Penghulu Kerajaan Mataram, Hijrah Demi Dakwah.
Mbah Canthing, menurut Murhardi, terpencar dari pasukannya saat memasuki wilayah Nganjuk. Kondisi Mbah Canthing saat itu sudah terluka parah setelah bertempur dalam sebuah peperangan. Ini karena badannya tertembak senapan tentara Belanda.
Saat lari menyelamatkan diri ke arah utara, darah segar terus mengucur dari badannya. Hingga pada suatu tempat yang sekarang dinamakan Desa Mlorah, darah yang keluar semakin deras dan terjatuh pingsan. Orang Jawa menyebut banyak darah yang keluar dengan istilah morah-morah. Kata ini, lambat laun, karena perubahan dialek dari masyarakat setempat, berubah menjadi mlorah.
Badan yang sudah kehabisan tenaga itu kemudian ditolong oleh penduduk sekitar dari kampung sebelah utaranya. Ini dilakukan agar dia tidak bisa ditemukan keberadaannya oleh pihak tentara Belanda. Dilihat dari pakaian kebesaran yang dikenakan, dia adalah sosok pimpinan dari keraton.
Prediksi ini benar adanya dan terbukti Mbah Canthing selamat dari kepungan tentara Belanda. Mbah Canthing akhirnya mampu menyambung hidupnya lagi. Tidak heran jika kampung sebelah utara Desa Mlorah yang sekarang itu kemudian dinamakan dengan Sembung.
Agar pengobatan dan pemulihan dari luka yang diderita bisa optimal, warga kemudian berinisiatif membawa Mbah Canthing kepada seorang tabib yang ada di utara Sembung. Keesokan harinya warga membuatkan tandu dari kayu untuk membawa ke tempat yang dituju.
Badan Mbah Canthing akhirnya diangkat bersama-sama untuk dinaikkan di atas tandu. Daerah lokasi sekitar rumah tabib yang tidak jauh dari Sembung itu kemudian dinamakan Ngangkatan. Itu karena warga beramai-ramai mengangkat badan Mbah Canthing untuk berobat ke situ.
Menyamar
Setelah sembuh, Mbah Canthing memulai hidup baru dengan menjadi rakyat biasa. Akhirnya dia membuka lahan baru di lokasi tempat dia terjatuh pingsan dan ditolong warga. Namun persisnya agak masuk ke barat. Meskipun saat itu lokasi yang ditempati masih berupa hutan belantara yang sangat angker.
Untuk mewujudkan tempat tinggalnya ini, Mbah Canthing dibantu istrinya yang bernama Mbah Sawi. Dia aslinya berasal dari daerah Bojonegoro. Mbah Sawi setia menemani suami tinggal di lokasi baru tersebut. Pada periode selanjutnya, Mbah Sawi inilah yang kemudian menjadi “orang pintar” sekaligus memimpin upacara-upacara adat yang digelar di Desa Mlorah. Terutama tradisi slametan untuk melaksanakan nadzar.
Dari pernikahan dengan Mbah Sawi, Mbah Canthing memiliki empat anak. Yaitu Mbah Ngalinem yang menikah dengan Suro Karso, Marijan, Madinem dan Simah. Keturunan Mbah Canthing sekarang banyak yang tinggal di Desa Mlorah. Rata-rata sudah berada pada generasi keempat dan kelima. Lokasi tinggalnya tidak berkumpul pada satu kawasan. Namun menyebar di beberapa tempat di Desa Mlorah, bahkan di beberapa dusun sekitar.
Meski demikian, di antara sesama keturunan Mbah Canthing masih saling mengenal antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak jarang pula mereka saling mempererat hubungan kekeluargaan itu dengan menikahkan antar keturunan. Saat salah satu keluarga punya hajat, biasanya saling mengundang.
Kemungkinan besar generasi penerus Mbah Canthing tidak ada yang berani tinggal di situ. Menurut Damis (2019), para keturunan Mbah Canthing kemudian bersepakat untuk mewakafkan tanah warisan itu bagi pengembangan Islam. Rencana itu dipelopori oleh Mbah Wariyem dan saudaranya, yang merupakan generasi ketiga dari Mbah Canthing, dari jalur Ngalinem. Tidak heran jika kemudian didirikan mushala dan beberapa ruang untuk mengaji.
Setiap setelah Maghrib malam Jumat, menurut KH Riyanto (2017), digelar tahlil kirim doa kepada para pendiri Desa Mlorah. Khusus malam Jumat Pahing, karena bertepatan dengan “hari kelahiran” Desa Mlorah, kirim doa digelar di joglo timur makam Mbah Canthing. Biasanya diikuti jamaah pengajiannya, tidak hanya diikuti warga Mlorah saja.
Upaya itu dilakukan untuk menjaga spirit nilai-nilai luhur yang sudah ditanamkan Mbah Canthing bagi warga Desa Mlorah. Ini mengingat Mbah Canthing sebenarnya bukan sembarangan.
Nama asli Mbah Canthing adalah Tumenggung Sri Moyo Kusumo. Gelar tumenggung di depan namanya menunjukkan cukup tinggi derajat dari trah bangsawan Jawa Islam. Biasanya, gelar tumenggung dipakai seorang kepala daerah di wilayah yang relatif jauh dari ibu kota kerajaan atau wilayah perbatasan.
Bahkan Imam Hartoyo (2019), ketua MWC NU Rejoso, mengidentifikasi Mlorah sebagai desa dengan sejarah panjang. KH Abu Hakim Abdurrahman (almarhum) dari Pesantren Sekapurtih Nganjuk diakui pernah menjelaskan secara detail kronologi sejarah Desa Mlorah dan tahun ringkasan kisah munculnya nama Mlorah. Termasuk tokoh-tokohnya, termasuk sosok yang disebut sebagai wong ning pojok’an deso.
Mbah Canthing sudah memberikan banyak teladan. Bahwa perjuangan harus dilakukan secara total dan berkelanjutan. Meski namanya tidak harus ditulis dalam buku-buku sejarah yang dibaca generasi penerus. Tapi spirit pengabdian bagi sesame manusia harus terus menyala.
Panelis Debat Calon Bupati Nganjuk (2024)